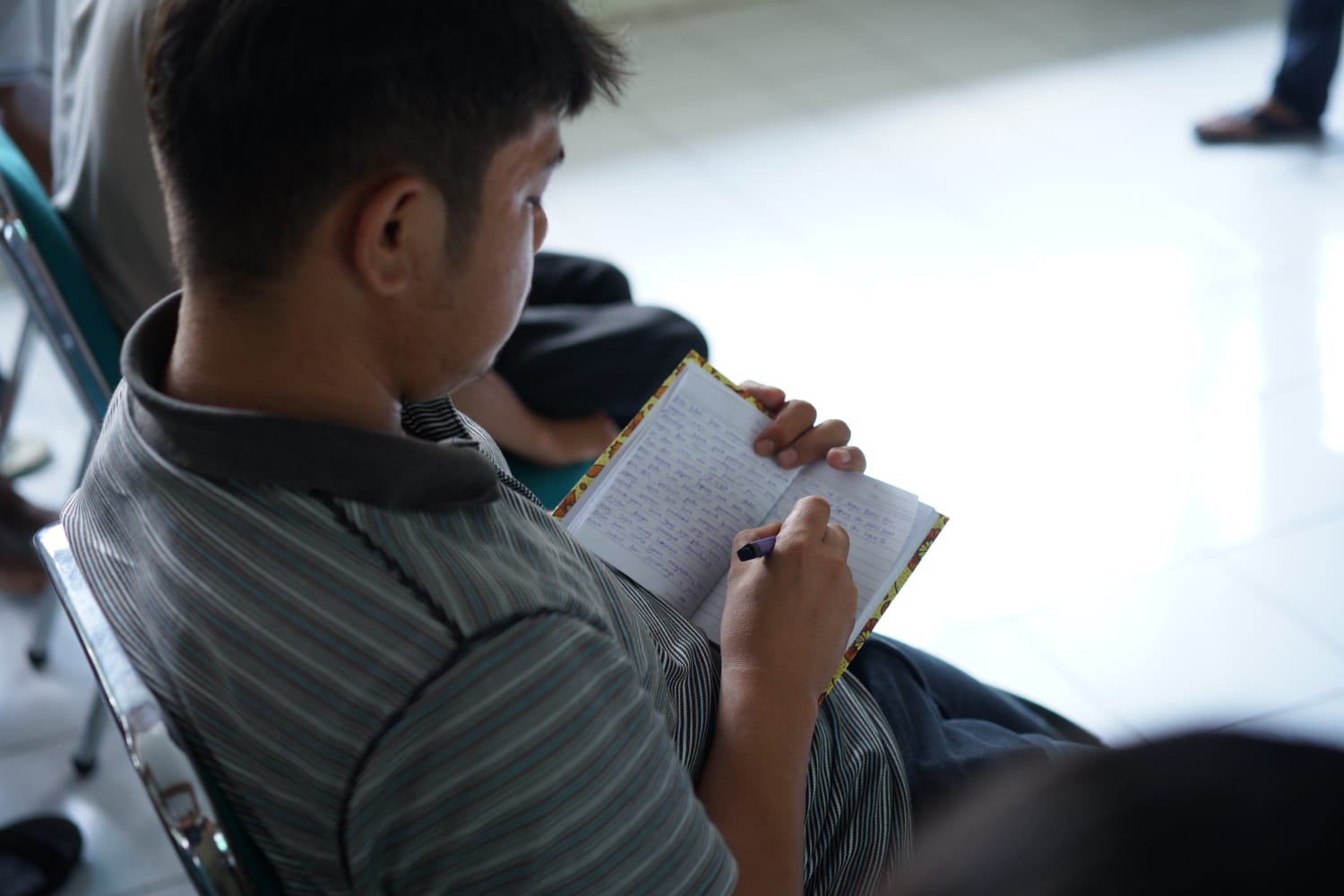SuaraIndo.Id – Fritzh Heber dan Carl Bosch nama yang mungkin asing. Tapi nitrogen sintetik temuan mereka merubah sistem pertanian global serta fondasi dominasi ekonomi politik Amerika Serikat di dunia. Tahun 1909, Fritzh Heber mengembangkan proses ekstraksi dan pemurnian nitrogen dari udara. Kemudian pada tahun 1910, Carl Bosch menyempurnakan metodenya untuk skala industri. Metode ini dikenal sebagai proses Heber-Bosch.
Baik Heber maupun Bosch mereka berdua bekerja untuk Badische Anilin- und Sodafabrik (BSAF). BSAF sendiri merupakan sebuah perusahaan kimia besar yang terlibat dalam pengembangan bahan kimia strategis untuk kebutuhan Jerman dalam Perang Dunia I (1914-1918). Pada awalnya temuan Heber-Bosch ini hendak digunakan sebagai bahan peledak.
Namun tahun 1920-an pasca kekalahan Jerman dalam PD I, temuan mereka diambil sekutu dan digunakan untuk pertanian negara Eropa Barat. Kemudian pada tahun 1939 juga dipakai dan dikembangkan di Amerika Serikat guna meningkatkan produksi untuk suplai pangan perang. Peningkatan produktifitas pangan inilah yang menjadi senjata tersembunyi AS dalam menaklukan dunia di Perang Dunia II (1939-1945) dan juga Perang Dingin (1947-1991).
Sebenarnya sebelum 1930 produksi pangan Amerika Serikat telah mengalami overproduksi karena kemajuan teknologi pertanian dan perluasan lahan pertanian. Saat terjadi great depression 1930-an daya beli atas pangan menurun dan petani AS bangkrut. Pemerintah Roosevelt membuat kebijakan Agricultural Adjustment Act (AAA)’33. Kebijakan ini memaksa petani untuk menunda tanam serta pemusnahan hasil produksi dan ternak lewat mekanisme pembayaran dari pemerintah.
Kebijakan Amerika Serikat ini berhasil memulihkan harga komoditas dan juga memberikan keuntungan bagi petani AS. Di sisi lain kebijakan ini bertentangan dengan etika global sebab banyak negara sedang dilanda krisis kelaparan pada masa itu. Di Ukraina (Uni Soviet) 7 juta nyawa melayang karena kelaparan dan malnutrisi. Di China pasca banjir besar Sungai Yangtze 1931 lahan pertanian rusak menimbulkan kelaparan dan menelan jutaan korban jiwa.
Efek domino great depression ke negara lain, krisis pangan di berbagai kawasan, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah agresi militer, dendam Jerman karena Perjanjian Versailes, serta absennya Amerika Serikat sebagai penengah konflik global, memberi ruang untuk lahirnya pemerintahan fasis di Jerman, Italia dan Jepang.
Invasi Jerman ke Polandia 1 September 1939 penanda dimulainya PD II. Secara geografis AS berada jauh dari zona perang karena itu produktivitas pangan mereka aman. Lahirlah kebijakan Lend-Lease Act (Maret 1941) yaitu ekspor bantuan pangan dan logistik untuk negara sekutu tanpa terlibat perang. Barulah saat serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 AS terlibat langsung pada PD II.
Saat AS terlibat perang muncul masalah yaitu berkurangnya tenaga kerja pertanian karena rekrutmen militer. Untuk mengatasi itu ditariklah perempuan dan kelompok minoritas ke dalam sektor pertanian, adopsi teknologi pertanian modern; traktor, mesin panen, dan pupuk sintetik. Juga ada kampanye Victory Garden yaitu ajakan agar warga sipil menanam sayuran di halaman rumah. Setelah PD II berakhir tahun 1945, kukuhlah posisi geopolitik Amerika Serikat lewat diplomasi pangannya.
Revolusi Hijau Penetrasi Menuju Kontrol Pangan Global
Menyambut narasi krisis pangan pasca perang, sejak tahun 1940 Amerika Serikat telah memulai proyek besar benama “Revolusi Hijau”. Revolusi Hijau adalah upaya menghadapi krisis dengan mengubah pertanian alamamiah menjadi pertanian berbasis ilmiah. Pijakan dari Revolusi Hijau adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kata lain menghapus pertanian tradisional. Pertama kali diterapkan di Meksiko pada Februari 1943 dengan nama Mexican Agricultural Program, didanai oleh Rockefeller Foundation, dikepalai oleh Norman Bourlaug.
Boulaug seorang ahli agronomi dan fitopatologi, ia berhasil menciptakan bibit gandum semi-kerdil Meksiko tahun 1955. Gandum jenis ini memiliki tangkai yang kuat, tahan penyakit dan responsif terhadap pupuk sintetis dan irigasi. Setahun setelah itu Meksiko mengalami swasembada pangan. Keberhasilan Meksiko ini mendorong ekspansi global. Tahun 1966, Ford Foundation juga ikut menjadi pendonor dalam riset Revolusi Hijau.
Kemudian bibit gandum hybrida dibawa ke India dan juga mengalami keberhasilan. Dari tahun 1965-1986 produksi gandum di India meningkat lebih dari 400% menjadikan India negara pengekspor gandum terbesar ke-tiga di dunia. Selain di India, sejak 1965 Pakistan juga mengalami peningkatan produksi dengan budidaya gandum hybrida ini.
Untuk ekspansi di Asia Tenggara, riset beralih dari gandum menjadi padi karena kawasan ini mayoritas mengkonsumsi nasi. Lewat pendanaan internasional Rockafeller Foundation dan Ford Foundation serta pemerintah Filipina, lahirlah lembaga riset International Rice Research Institute (IRRI). Dari riset IRRI berkembanglah padi jenis IR8. Karakteristiknya sama dengan gandum semi-kerdil di Meksiko, yaitu adaptif terhadap irigasi, input pupuk sintetik dan pestisida dengan kemampuan produksi tinggi.
Di Indonesia sendiri penerapan Revolusi Hijau tahun 1966 berhasil membuat Indonesia mengalami swasembada beras tahun 1984. Bedanya penerapan Revolusi Hijau Indonesia sangat militeristik. Militer terlibat langsung lewat komando teritorial dalam program pertanian seperti Bimbingan Massal (BIMAS)’66 dan Intensifikasi Khusus (INSUS)’79. Petani diarahkan secara top-down dengan pengawasan ketat angkatan bersenjata di lahan mereka.
Lahirnya Sistem Agribisnis dan Rezim Pangan Ke-3
Tahun 1954 muncul Public Law 480 (PL-480) sebuah program diplomasi gandum Amerika Serikat yang menyasar negara-negara berkembang. Selain untuk ekspansi produk pangan AS juga berguna untuk menghambat penyebaran paham komunisme dari Uni Soviet, musuh AS dalam Perang Dingin. Negara-negara inilah yang nanti mengadopsi Revolusi Hijau.
Jika di Eropa Barat ada Marshall Plan’48 yang menyalurkan bantuan pangan dan pendanaan pembangunan dan perbaikan ekonomi pasca PD II, di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan juga ada bantuan sejenis dari Economic Coorperation Administration (ECA) tahun 1950-an dan otomatis ketiga negara juga menerapkan Revolusi Hijau namun dengan nama yang berbeda-beda. Merekalah yang nanti diglorifikasi dan menjadi model industrial untuk Asia.
Penerapan Revolusi Hijau tidak bisa dilepaskan dari paket Revolusi Hijau yaitu seperangkat teknologi pendukung seperti bibit unggul, pupuk sintetis, racun dan obat pertanian serta mesin, energi dan irigasi. Semua kebutuhan itu dipenuhi oleh perusahaan pertanian global seperti Monsanto, Syngenta, Cargill, DuPont, Bayer AG, dan perusahaan minyak serta perbankan. Mereka semua adalah perusahaan besar yang bermain dalam PD I dan PD II.
Integrasi pertanian ke dalam pasar bebas disusun lewat General Agreement on Tarif and Trade (GATT)’47, berisi perjanjian multilateral liberalisasi perdagangan. Tahun 1986-1994 GATT putaran Uruguay, perjanjian meluas hingga ilmu pengetahuan dan jasa di sektor pertanian. Juga didirikannya World Trade Organization (WTO)’95. WTO kemudian memberlakukan Agreement on Agriculture (AoA)’95 yaitu kontrol atas subsidi dan tarif serta mendorong liberalisasi perdagangan sektor pertanian global.
Dalam pendanaan guna menciptakan keberlanjutan dan ketergantungan global, tahun 1944 diadakan Konferensi Bretton Woods. Diadakan oleh negara-negara sekutu guna membentuk tatanan ekonomi global baru pasca PD II. Dari perjanjian ini dolar menjadi mata uang dunia dan lahirlah International Monetery Fund (IMF) dan World Bank (WB). Setiap peminjam harus mendukung privatisasi, deregulasi dan pengurangan subsisi ala neoliberalisme.
Menurut Philip McMichael dalam bukunya Rezim Pangan dan Masalah Agraria, secara global pasca diplomasi pangan dan pendanaan AS hingga terbentuknya sistem neoliberal yang kuat, terjadi transisi menuju Rezim Pangan ketiga. Inggris dan Amerika Serikat adalah rezim pangan pertama dan kedua yang bercirikan kontrol negara atas pangan dunia. Namun di rezim ketiga yang terjadi adalah kontrol korporasi global atas pangan dalam kerangka agribisnis.
Gerakan Petani Sebagai Bentuk Contra Hegemony Agribisnis
Sistem agribisnis ini tidak sedikitpun menguntungkan petani kecil, hanya efektif bagi perusahaan pertanian dengan modal dan lahan yang mendukung. Model pertanian agribisnis menimbulkan kerusakan lingkungan, penghancuran kebudayaan, hilangnya pengetahuan dan bibit lokal, pangan tidak sehat, ketergantungan dan biaya mahal, perampasan lahan petani dan masyarakat adat untuk ekspansi industri pertanian yang kemudian menjurus pada kemiskinan struktural.
Dampaknya pada negara berupa akumulasi hutang yang semakin besar terhadap institusi keuangan global. Negara-negara yang pernah swasembada pangan dengan menerapkan Revolusi Hijau sekarang terjerumus kepada ketergantungan impor pangan yang semakin ekstrim. Contoh jelasnya Indonesia hari ini yang tidak bisa lepas dari skema hutang dan ketergantungan impor pangan yang semakin meningkat.
Keresahan-keresahan ini kemudian mencuat secara global dan terkonsolidasi tahun 1993 di Mons, Belgia. Gerakan ini dikenal sebagai La Via Campesina, sebuah wadah yang menampung aspirasi gerakan-gerakan petani di berbagai negara di dunia. Mereka adalah bentuk kontra-hegemoni yang sistematis atas wacana agribisnis. LVC gencar melakukan penolakan atas WTO, kampanye anti-GMO dan advokasi atas hak petani.
La Via Campesina mendukung agroekologi yang menjadi lawan dari agribisnis. Membangun kesadaran akan pentingnya hak atas tanah kedaulatan benih dan kedaulatan pangan serta merawat pengetahuan lokal. Petani beserta benih dan lahan tidak hanya sekedar objek dan alat produksi semata, mereka merupakan subjek global yang berhak bersuara dan menentukan nasib dalam politik global.
Salah satu keberhasilan LVC adalah United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) di PBB tahun 2018. Isinya mencakup pengkuan hak atas tanah, benih, pangan dan lingkungan sehat, pengakuan hak kolektif komunitas adat dan petani kecil serta kewajiban negara melindungi dan memenuhi hak tersebut. Menyuarakan pentingnya ruang alternatif bagi sistem pangan yang adil dan berkelanjutan.
Di Indonesia, ada Serikat Petani Indonesia (SPI) sebuah organisasi petani yang tergabung ke dalam La Via Campesina. Organisasi ini baru saja melakukan Kongres ke-V di provinsi Jambi dari tanggal 20-25 Juni 2025. Dihadiri petani anggota SPI dari 29 Provinsi, mereka bertemu dan berkumpul memilih ketua umum dan kepengurusan, menyusun AD/ART dan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) serta menentukan pandangan dan sikap politik organisasi untuk lima tahun ke depan.
SPI aktif dalam memperjuangkan reforma agraria dan kedaulatan pangan, mendirikan Koperasi Petani Indonesia yang terintegrasi sampai ke basis. Lahan hasil perjuangan nantinya harus mampu menghasilkan produk yang akan didistribusikan lewat ekosistem koperasi. Ini berguna untuk membangun ekonomi kerakyatan. Beberapa koperasi SPI telah berjalan dan berbadan hukum dengan lini usaha masing-masing.
Kongres V SPI ini juga mewadahi suara pemuda tani dan perempuan tani. Kelompok yang terdampak langsung kebijakan neoliberal pertanian yang semakin ganas. Permasalahan yang mereka hadapi adalah susahnya akses ke lahan dan pemodalan untuk pertanian serta kegiatan bertani yang mahal dan tidak menguntungkan. Inilah faktor yang menyebabkan semakin berkurangnya regenerasi petani muda di Indonesia.
Sebagai aktor penting dalam mendorong deklarasi UNDROP di PBB, SPI lewat Kongres V akan semakin gencar menyuarakan hak-hak petani baik di tingkal lokal sampai internasonal dan berupaya aktif dalam persatuan politik dan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
Refleksi Sebelum 80 Tahun Kemerdekaan Kita
Pernahkah anda melihat para petani dari berbagai provinsi berkumpul dan membicarakan permasalahan mereka, menyusun AD/ART, GBHO, ekonomi kerakyatan bahkan penetuan sikap politik? Membicarakan hak atas tanah, benih, pangan, pengetahuan lokal, masyarakat adat dan masa depan generasi dalam sebuah forum nasional? Pembicaraan yang asing dalam benak pemerintah kita yang keracunan neoliberalisme.
Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 04 Oktober 2024 merilis “61 Persen Anggota DPR 2024-2029 Merupakan Politisi Pebisnis”. Bayangkan di negara republik, dapur kebijakan yang harusnya menyajikan Rancangan Undang-Undang yang menyehatkan publik telah berubah menjadi sektor privat. Tentu di sana kebijakan yang dibuat hanyalah kebijakan pesanan dari orang-orang yang mampu mengaksesnya dengan uang. Siapa lagi kalau bukan korporasi global, mereka mengubah pemerintah kita menjadi alat akumulasi kapital semata.
Hampir 80 tahun kita merdeka namun nasib petani semakin parah, siapa lagi yang akan mewakili mereka jika bukan mereka dan orang-orang yang senasib serta yang mengerti penderitaan mereka? Pemerintah hari semakin jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. Ini mengingatkan kita atas pernyataan Bung Karno “perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”.
Namun, jika anda melihat para petani berserikat dan berkumpul, membicarakan nasib mereka sendiri dalam forum nasional, berdebat panas dan menghasilkan kesimpulan bersama, saat itulah anda akan menyadari bahwa harapan para pendiri bangsa masih hidup. Harapan besar yang dirawat tangan-tangan kecil di pedesaan, di pemukiman tidak layak perkotaan, di pesisir pantai yang panas, dan di dalam hutan masyarakat adat yang hening. Menunggu untuk disemai dan dibesarkan oleh orang banyak sebelum akhirnya kita panen bersama dalam sebuah kedaulatan dan kemerdekaan yang sejati.
“Siapa yang memguasai benih maka ia akan menguasai pangan, siapa yang menguasai pangan maka ia akan menguasai perut, siapa yang menguasai perut maka ia akan menguasai politik, siapa yang menguasai politik maka ia akan menguasai dunia”
Penulis
Andrezal
Daulat Institut/Peserta Kongres V SPI